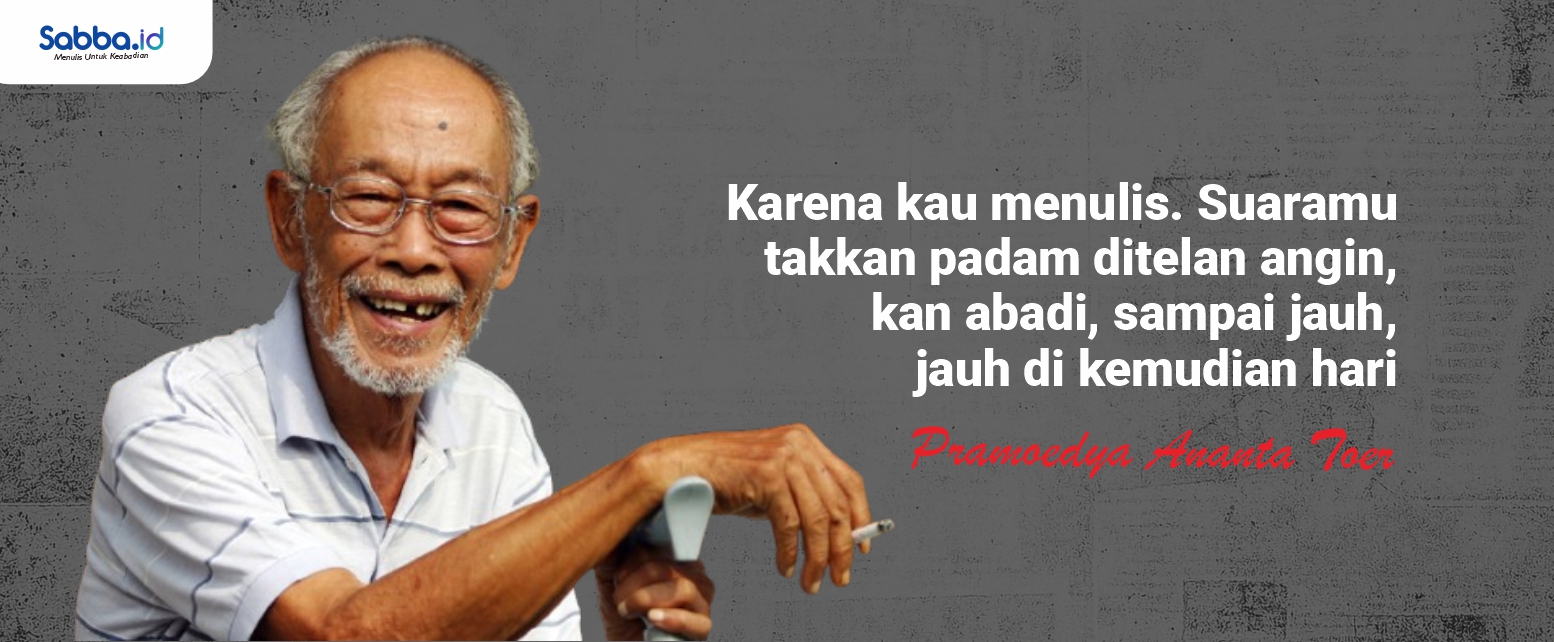Pengurus Kumandang Banten: Mengapa Kita Rela Jadi Tong Sampah?

Impor sampah Tangsel ke Pandeglang memicu gejolak warga karena disatu sisi bisa menjadi tambang PAD disisi lain dapat menjadi jebakan lingkungan atau bahkan celah korupsi. Tanpa transparansi, kesiapan teknis, dan partisipasi publik, kebijakan ini hanya akan memperburuk masalah yang sebenarnya ingin diatasi.
Sampah di negeri ini Banten khususnya, bukan sekadar limbah fisik—ia adalah limbah kebijakan, limbah kesadaran, dan limbah kepemimpinan. Di balik gunungan sampah plastik dan organik, tersembunyi jejak ketidakseriusan pemerintah dalam menata sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
Transfer Sampah, Transfer Masalah
Kejati (Kejaksaaan Tinggi) Banten merilis informasi dugaaan korupsi berjamaah DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Tangsel (Tangerang Selatan) pada 21 April 2025. Ditengah skandal proyek pengelolaan sampah senilai hampir Rp76 miliar yang berujung pada dugaan korupsi belum hilang, Tangsel justru sibuk mendorong kebijakan pemindahan sampah ke Pandeglang.
Ketika TPA Cipeucang Tangsel kelebihan kapasitas dan dikelola seadanya, solusinya bukan membangun sistem baru melainkan memindahkan masalah ke tetangga.
Pertanyaannya sederhana: kenapa harus dipindah? Jawabannya pedih karena Tangsel gagal menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukannya menata ulang sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, mereka memilih jalan pintas: buang ke daerah yang lebih lemah tawar- menawarnya. Pandeglang jadi sasaran. Seolah-olah wilayah dengan indeks pembangunan rendah merujuk data–BPS (Badan Pusat Statistik) Banten 2023– itu pantas dijadikan tempat buangan, asal diberi kompensasi. Lebih menyakitkan lagi, pemindahan ini dibungkus narasi ‘kerja sama antar daerah’ dan ‘peningkatan PAD’. Padahal, realitasnya adalah transfer beban ekologis dari kota kaya ke kabupaten yang bahkan belum mampu menyelesaikan sampahnya sendiri. Ini bukan kolaborasi, ini kolonialisasi lingkungan dengan dalih birokrasi.
Sampah Diseret ke Daerah, PAD Dijadikan Dalih
Mengutip Detik.com Wakil Bupati Pandeglang menuturkan “Untuk per hari akumulasinya dari Tangerang Selatan sekitar 300 sampai dengan 500 ton, tapi inikan baru targetan. PAD Rp 9 miliar kalau targetan 500 ton perhari bisa terpenuhi pengiriman dari Tangerang Selatan,”.
Dengan dalih kerja sama antar daerah dan janji kompensasi miliaran rupiah, Pandeglang bersedia menerima 500 ton sampah per hari, bukan dari warganya sendiri, tapi dari kota dengan APBD jauh lebih besar. Pertanyaannya: kenapa mau?
Jawaban formalnya mudah ditebak: ada anggaran masuk, ada perbaikan TPA, dan ada potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tapi jawaban yang lebih jujur tak akan seindah itu. Pandeglang menerima sampah bukan karena siap, melainkan karena Lemah – lemah dalam keberpihakan terhadap rakyat.
Sampah Kiriman, Risiko Ikutan
Mari bicara apa adanya: ini bukan kerja sama, ini penyerahan ruang hidup.
Pandeglang belum selesai menyelesaikan persoalan sampah lokal truk sampah masih terbatas, pengangkutan belum menjangkau seluruh kecamatan, dan pengelolaan TPA Bangkonol masih menggunakan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan. Namun justru di tengah keterbatasan itu, pemerintah daerah malah membuka gerbang selebar-lebarnya bagi sampah impor dari kota tetangga yang kaya.
Apakah hanya karena kompensasi Rp40 miliar selama tiga tahun, pemerintah daerah bersedia menukar udara bersih dengan bau menyengat, tanah subur dengan limbah, dan kesehatan warganya dengan risiko jangka panjang? Jika iya, maka ini bukan keputusan strategis, tapi kompromi yang merusak martabat kebijakan publik.
Partisipasi Publik dan Jalan Tengah Penyelesaian
Pandeglang sedang menghadapi ujian besar, jika pemerintah daerah tidak membatalkan atau setidaknya mengevaluasi ulang kerjasama ini secara terbuka, maka yang diterima bukan hanya sampah Tangsel—tapi juga dampaknya yang menumpuk dan tak bisa didaur ulang.
Masyarakat dibiarkan bingung, tanpa edukasi dan fasilitas yang memadai. Sementara itu, kebijakan hanya hadir di atas kertas, tak berakar di lapangan. Padahal dampaknya nyata: banjir karena saluran mampet, udara yang kotor hingga air tercemar. Kebijakan yang menyangkut ruang hidup seharusnya melibatkan rakyat. Tapi dalam kasus penerimaan sampah dari Tangsel ke Pandeglang, justru yang terjadi adalah kebalikan: kesepakatan dibuat di ruang tertutup, sementara rakyat hanya jadi penonton—atau lebih tepatnya, korban.
Belum lagi potensi korupsi yang akan terjadi kedepan jika diawal saja publik tidak dilibatkan secara menyeluruh.
Ini bukan lagi soal siapa yang membuang, tapi siapa yang membiarkan. Jika publik hanya menonton dan abai terhadap proses pengawasan-nya, maka sampah dan potensi korupsi akan menjadi warisan paling busuk yang ditinggalkan.
Oleh : Doni Nuryana