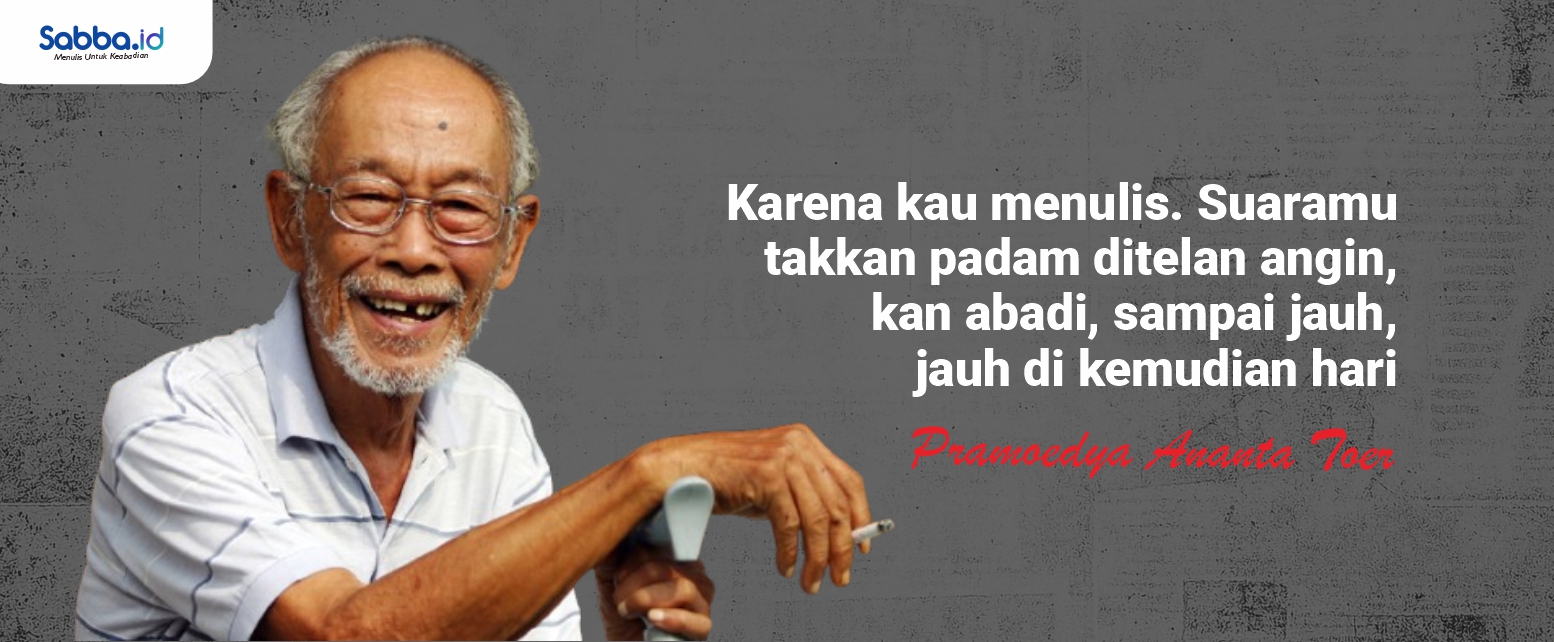Ahmad Arif Agustin: Pemilu sebagai Instrumen Etika Politik: Telaah Filosofis atas Legitimasi Kekuasaan

SABBA.id, – Di tengah hiruk-pikuk wacana pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, kita sering terjebak pada perdebatan teknis: efisiensi anggaran, beban penyelenggara, atau kestabilan pemerintahan. Padahal, di balik itu terselip pertanyaan mendasar yang bersifat filosofis: Untuk apa sebenarnya kita bernegara dan mengadakan pemilu? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan titik mula bagi setiap pembuat kebijakan untuk menimbang arah demokrasi.
Filsuf politik seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mengajarkan bahwa legitimasi kekuasaan bertumpu pada consent of the governed persetujuan rakyat yang diberikan melalui mekanisme perwakilan. Pemilu, dalam kerangka ini, bukan sekadar prosedur memilih wakil, tetapi instrumen untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak tercerabut dari akarnya. Jika pemilu diatur hanya berdasarkan pertimbangan teknis tanpa mengindahkan prinsip filosofisnya, maka yang tersisa hanyalah ritual demokrasi tanpa ruh kebajikan publik.Di sisi lain, Aristoteles menempatkan politik sebagai seni mengelola polis demi eudaimonia kehidupan yang baik. Maka, baik pemilu nasional maupun lokal semestinya diarahkan untuk memastikan keadilan distribusi kekuasaan dan kesempatan. Pemisahan pemilu mungkin menjanjikan fokus yang lebih tajam antara isu nasional dan lokal, tetapi ia juga berpotensi memperlebar jarak psikologis antara warga dan institusi negara jika tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai.
Dalam konteks Indonesia, pemilu serentak 2019 telah menunjukkan betapa rumitnya mengelola beban kerja, logistik, dan kompleksitas penghitungan suara. Namun, memisahkan kembali pemilu tanpa evaluasi filosofis berisiko mengulangi kesalahan lama: menata demokrasi hanya di atas papan catur kepentingan praktis. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: apakah desain pemilu kita telah memaksimalkan partisipasi substantif warga negara, ataukah ia hanya memudahkan manuver politik elit?Pandangan filsafat politik mengingatkan kita pada tiga hal. Pertama, kebijakan pemilu harus menjunjung prinsip justice as fairness seperti diungkapkan John Rawls di mana setiap warga memiliki peluang yang setara untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Kedua, demokrasi bukan sekadar counting votes tetapi weighing voices menghitung dan menimbang suara berdasarkan kualitas representasi. Ketiga, kebijakan pemilu harus mampu menumbuhkan civic virtue, kebajikan warga yang mendorong keterlibatan aktif dan bertanggung jawab. Karena itu, keputusan untuk memisahkan atau menyatukan pemilu seharusnya tidak hanya lahir dari kalkulasi politis atau administratif, melainkan dari refleksi mendalam: apakah desain itu mampu menguatkan legitimasi, memperkokoh persatuan, dan menghidupkan semangat kebajikan publik? Tanpa itu, demokrasi kita berisiko menjadi panggung lima tahunan yang meriah di permukaan, namun rapuh di dasar pondasinya.
Mungkin inilah saatnya kita mengingat kembali pesan Bung Hatta: “Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi bagaimana kita hidup bersama secara adil.” Dalam kacamata filsafat, pemilu adalah cermin moral bangsa. Jika cermin itu buram, maka yang perlu dibenahi bukan hanya pantulan, tetapi juga cara kita merawatnya.
Oleh: Ahmad Arif Agustin,S.Pd.I.,M.H.Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Provinsi Banten
tulisan tersebut tidak termasuk mewakili redaksi