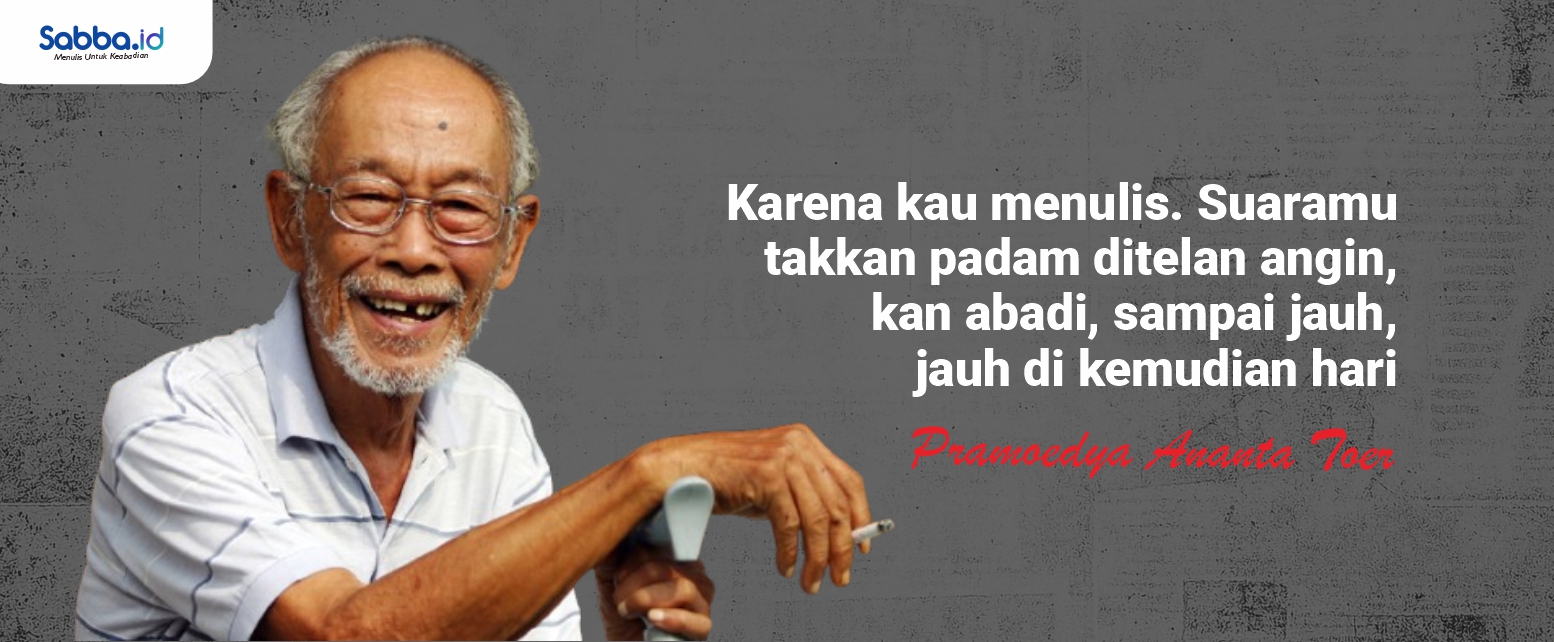Muhammad Ervin Nizar: Nada Sorga di Atas Lemur

Penulis: Muhammad Ervin Nizar, bergiat di Kumandang PW Serang.
Lembur Cipapare masih berselimut kabut ketika Santim menurunkan kacapi dari loteng rumah panggungnya. Jemarinya bergetar halus, entah karena usia atau karena kenangan yang mendadak tumpah dari senar kayu tua itu. Di luar, ayam mulai berkokok-bersautan, dan embun menggantung di ujung-ujung daun nangka.
Sudah bertahun-tahun kacapi itu tak dimainkan. Sejak istrinya, Euis, berpulang, Santim lebih banyak duduk termenung, mendengarkan angin yang lewat seperti nada-nada yang hilang. Tapi pagi itu berbeda. Sebuah pesan dari anaknya, Andri, membuatnya menurunkan kacapi dan mengelapnya pelan.
“Pak, minggu ini saya pulang. Mau rekam Bapak main kacapi, buat tugas dokumenter kampus. Temanya: warisan budaya Sunda.”
Santim tersenyum samar membaca pesan itu malam sebelumnya. Anak satu itu memang jarang pulang. Sejak merantau ke Bandung dan masuk dunia musik digital, dunia Andri makin berbeda. Beda dari dulu, waktu kecil, saat Andri sering duduk di pangkuannya, mendengarkan pupuh Kinanti sambil menepuk-nepuk kacapi kecil mainan.
“Bapak hayang maén deui?” tanya Ani, cucunya, saat melihat Santim duduk di bale bambu tua yang hampira roboh, menyetem kacapi dengan telinga sedikit didekatkan.
“Henteu hayang… tapi kudu,” jawab Santim pelan.
“Kenapa kudu?”
Santim tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke sawah yang baru saja dipanen. Suara bel cicit sapi terdengar dari kejauhan, bersahut-sahutan dengan angin yang membawa bau rumput basah.
“Upami urang teu nyekel deui, saha deui nu rek ngajaga?” gumamnya.
Ani mengangguk-angguk, semacam setengah mengerti. Ia baru kelas enam SD, tapi cukup sering mendengar tembang dari kakeknya—meski lebih sering sambil main gawai.
Hari itu Santim berlatih. Satu pupuh, dua pupuh. Kadang berhenti, kadang meneteskan air mata. Bukan karena salah nada, tapi karena suara kacapi itu membawa kembali kenangannya dengan Euis yang dulu selalu bersuara merdu menyanyikan Pupuh Dandanggula setiap kamis malam.
Hari Minggu datang. Andri pulang membawa alat rekaman, kamera kecil, dan laptop dan seperangkat kebutuhan yang lainnya. Ia datang bersama temannya, Dara, mahasiswa etnomusikologi.
“Assalamualaikum, Pak!” sapa Andri sambil menaruh ransel besar. “Saya cuma sebentar, ya. Mau ambil footage dan rekam suara. Nanti saya edit di Bandung.”
Santim mengangguk pelan. Ia tak banyak bicara, hanya menyodorkan kopi dan mengajak duduk di ruang tengah yang temaram dan di kursi kayu yang mulai keropos.
Rekaman dimulai. Santim memainkan pupuh Kinanti, lalu Sinom, dan terakhir Asmarandana. Jemarinya yang renta tetap menari lembut. Di belakang kamera, Dara beberapa kali mencatat. Andri? Ia hanya sesekali melihat layar, lalu mengangguk singkat.
Setelah selesai, Andri berdiri.
“Cukup, Pak. Makasih, ya. Nanti saya kabari kalau videonya jadi.”
Andri hanya tersenyum kecil.
Malamnya, Santim duduk sendiri di bale. Kacapi diletakkan di sampingnya, seperti sahabat tua yang tak ingin dilepas.
“Andri ayeuna sibuk,” gumamnya. “Tapi meureun, nu salah teh, bapak… henteu ngajarkeun cukup waktu.”
Tiba-tiba langkah kecil terdengar. Ani datang, membawa kacapi mainan miliknya yang dulu diberi Santim waktu ulang tahun kelima.
“Bapak,” katanya pelan, “Ani rek diajar kacapi, nya?”
Santim menoleh. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia tersenyum lebar.
“Hayu, urang mimiti ku pupuh Kinanti heula.”
Malam itu, di tengah angin dan rintik-gemercik-hujan dan suara jangkrik yang sedikit nyaring, dua generasi bersuara dalam satu alunan.
Beberapa bulan kemudian, Andri mengirim tautan video.Judulnya:
“Kacapi di Atas Lembur: Warisan yang Hampir Hilang”
Video itu viral. Santim mendengarnya dari tetangga yang menunjuk-nunjuk layar ponsel.
Tapi bukan itu yang membuat Santim menangis.
Ia menangis saat melihat bagian akhir: Ani, duduk di panggung kecil saat pentas budaya desa, memainkan kacapi warisan leluhurnya. Pupuh yang dimainkan: Dandanggula, tembang kenangan bersama Euis.
Di antara penonton, Santim berdiri diam. Dadanya penuh. Bukan bangga. Bukan haru. Tapi lega.
Karena kini ia tahu, suara kacapi tidak akan hilang begitu saja. Di atas lembur, selalu akan ada yang mendengarnya kembali; mendengar nada sorga.