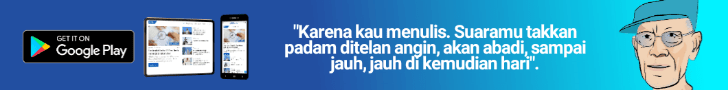SABBA.ID | Serang – Pernyataan Menteri Agama Yakut Cholil Qoumas ini menjadi buah bibir, terutama ketika terujar suara gonggongan anjing, yang bersamaan dengan konteks peraturan pengeras suara. Anehnya tiba-tiba muncul di berbagai media seolah-olah Menteri Agama mempersamakan suara Azan dengan suara Anjing.
Sontak, sebagian masyarakat seperti menyantap makanan lapar dengan tergesa-gesa menelanya tanpa mengunyahnya, terutama bagi pemangku kepentingan “gorengan isu sara”.
Dengan penasaran, saya pun mencari-cari video utuhnya. Di media sosial ternyata durasinya kurang lebih dua menit lima puluh detik.
Berikut petikan isi videonya: “Oh iya, iya. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan, kita tidak melarang Masjid, Musala menggunakan toa, tidak, Silahkan. Karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam. Tetapi, ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, toanya gitu gak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur kapan mereka mulai bisa menggunakan sepiker itu sebelum azan dan setelah azan.”
Bagaimana menggunakan speaker dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis. Meningkatkan manfaat mengurangi mafsadat, jadi meningkatkan manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan.
Karena kita tahu, misalnya yang berada di daerah mayoritas muslim. Hampir di setiap 100 meter, 200 meter itu ada Musala, Masjid. Bayangkan kalau kemudian di waktu bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas kaya apa? itu bukan lagi syiar tapi gangguan untuk sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim.
Saya hidup dilingkungan non muslim kemudian rumah ibadah saudara-saudara non-muslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan itu rasanya bagaimana. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita. Kalau kita hidup dalam satu kompleks itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua, misalnya. Menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu ga.
Artinya apa, suara-suara ini, apa pun suara itu ya. Ini harus kita atur. Supaya tidak menjadi gangguan. Sepiker di Musala dan di Masjid monggo dipakai, silakan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan sepiker sebagai sarana sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan, tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita.
Berbeda keyakinan harus kita hargai. Itu saja intinya. jadi saya kira, dukungan juga banyak atas ini, karena di bawah alam sadar kita kan ini mengakui, kawan-kawan wartawan ini pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti akan mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di suatu tempat, kemudian ada truk kiri, kanan kita, depan belakang kita, merekanya menyalakan mesin sama-sama pasti kita terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan untuk kita, gitu yah.
Apa yang keliru dari pernyataan tersebut? Padahal jika diamati, tidak ada pernyataan Gus Men itu menyinggung soal perbandingan azan dengan suara gonggongan anjing dalam satu ujaran yang sama, bahkan ia sama sekali tidak menyebut kata azan pada ujaran itu.
Dalam perspektif Tafsir Maqashidi, memahami suatu teks itu tidak didasarkan kepada juz’iyat al-kalam (kalimat parsial), karena akan menghilangkan al-maqasid al-‘ammah (tujuan umum) atau pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau pengucap secara utuh untuk sesuai maksud pengarang itu sendiri.
Sehingga pendekatan maqashidi ini adalah cara memahami teks yang tidak menghilangkan nilai-nilai mautul mu’allif (kematian pengarang), melainkan secara psikologis menyelami maksud kalimat berdasarkan pesan yang disampaikan pengarang tanpa mendistorsi makna.
Maka ujaran yang disampaikan Kementerian Agama, Jika dilihat dari perspektif maqashid al-‘amm, sangat keliru jika pernyataan tersebut disimpulkan suara azan dengan analogi gonggongan Anjing.
Coba perhatikan pada kalimat “Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim. Saya hidup dilingkungan non-muslim kemudian rumah ibadah saudara-saudara non-muslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita. Kalau kita hidup dalam satu kompleks itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua, misalnya. Menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu ga?”
Dalam ujaran ini sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, yang ada justru Gus Men menggunakan logika terbalik, dimana dirinya hidup dilingkungan non-muslim lalu kemudian di sana (lingkungan non-muslim) itu menyalakan sepiker dengan bersamaan, tentu menimbulkan ketidaknyamanan kepada yang berbeda keyakinan (dalam hal ini pengujar sendiri).
di situ kalimat berhenti, dan digantikan dengan jika ada suara anjing menggonggong di tengah suasana yang mestinya kondusif, maka bagaimana perasaan bagi yang tidak memiliki peliharaan anjing. Mungkin bagi si pemilik tidak menjadi masalah, tapi belum tentu yang tidak memiliki. Maka yang ditarik dalam hal ini adalah antara suara dan pendengar suara yang merasa terganggu karena ketidakteraturan suara itu.
Ia melanjutkan dengan analogi bisingnya suara anjing yang menggonggong mengganggu orang lain. Selain itu, Ia juga mempertegas “apa pun suara itu,” yang berarti tidak menunjuk pada satu objek. Bahkan ia mengandaikan kebisingan suara dengan mesin truk yang mengganggu suara sekitarnya.
Ini artinya, logika Gus Men ingin mengajak berpikir dari sudut pandang atau perspektif minoritas, di mana yang mayoritas itu tidak menunjukkan egoismenya di hadapan yang lain.
Saya mengandaikan, jika saudara hidup di tengah masyarakat yang berkeyakinan minoritas, kemudian di sekeliling saudara secara mayoritas berbeda keyakinan, lalu di setiap acara keagamaan memakai suara yang tidak diatur.
Bagaimana perasaan bagi orang tersebut. Secara Nurani yakin bagi minoritas itu kurang begitu nyaman, tapi tidak cukup nyali untuk menyampaikannya. Sehingga, pesan sesungguhnya yang ingin disampaikan Gus Men setidaknya adalah pertama, tidak ada pelarangan menggunakan pengeras suara sebagai syiar agama, tapi yang ada adalah pengaturan volumenya.
Bahkan ditegaskan oleh beliau sendiri tidak ada larangan, tapi peraturan tersebut semata-mata hanya membuat masyarakat hidup dengan harmonis.
Kedua, sejalan dengan kaidah درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح (menghilangkan mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat). Syiar Agama menggunakan pengeras suara tentu sangat bermanfaat dan penting sekali, supaya lebih terdengar panggilan beribadah atau lainya. Tapi menjaga kondusifitas dan kenyamanan jauh lebih penting diperhatikan untuk menghindari kemafsadatanya seperti, disharmonis karena dampak suara yang merasa terganggu.
Maka, poin penting dari Kementerian Agama adalah “niat menggunakan toa, menggunakan sepiker sebagai sarana sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan, tapa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita.”
Sungguh keji jika seseorang itu mendistorsi perkataan yang memang bukan makna sebenarnya. Karena ini adalah bagian dari pendustaan dan penghasutan.
Oleh : Salim Rosyadi
Sekretaris Rumah Moderasi Beragama (RMB) UIN SMH Banten